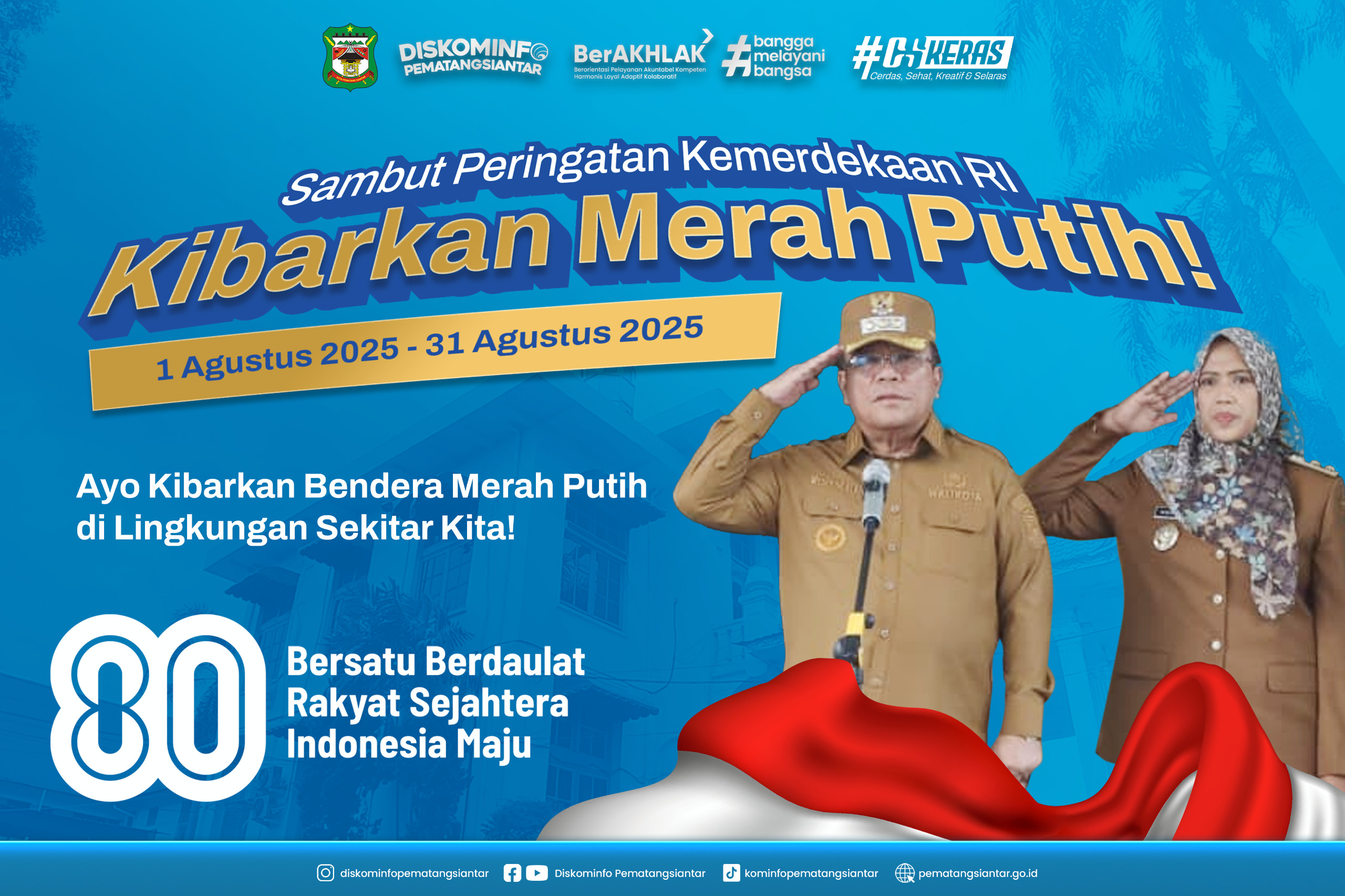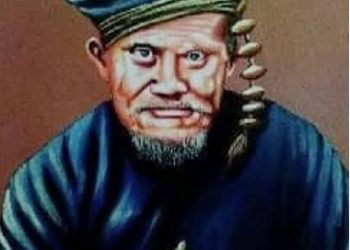PEMBANGUNAN pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, telah menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks.
Proyek yang menggunakan material bambu ini menimbulkan tanda tanya besar karena tidak ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya.
Meskipun kelompok bernama Jaringan Rakyat Pantura mengklaim membangun pagar tersebut secara swadaya, skala proyek ini membuat klaim tersebut diragukan banyak pihak.
Aspek Legalitas dan Kontroversi
Pagar laut ini menyoroti persoalan hukum dan tata kelola yang lemah. Berdasarkan laporan, proyek ini tidak memiliki dokumen izin resmi dari pemerintah. Hal ini melanggar Pasal 49 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur pemanfaatan ruang laut secara menetap harus sesuai dengan peraturan dan izin yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, bahkan penghentian kegiatan.
Selain itu, ditemukan adanya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area tersebut, yang mencapai luas hingga 300 hektare. Sertifikat ini diterbitkan untuk perusahaan swasta dan individu, yang menurut ahli hukum Abdul Fickar Hadjar, merupakan tindakan manipulasi ruang publik. Sertifikat ini dinilai batal demi hukum karena objek yang disertifikasi adalah area laut yang seharusnya menjadi milik negara. Kasus ini mengindikasikan adanya penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan potensi tindak pidana korupsi.
Dampak Lingkungan yang Memprihatinkan
Dari sisi lingkungan, pagar laut ini membawa dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut. Habitat alami biota laut terganggu akibat adanya penghalang fisik yang mengubah pola aliran air dan mengganggu siklus hidrologi. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan hidup organisme laut, tetapi juga memengaruhi keseimbangan ekosistem pesisir. Selain itu, limbah konstruksi dari bambu yang digunakan berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini menambah beban bagi ekosistem yang sudah rentan akibat aktivitas manusia lainnya, seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran dari daratan.
Konflik Sosial di Tengah Masyarakat
Pembangunan pagar laut juga memicu konflik sosial di antara masyarakat setempat. Sebagian masyarakat mendukung proyek ini karena diyakini dapat memberikan manfaat tertentu, seperti perlindungan wilayah dari abrasi. Namun, sebagian besar masyarakat, terutama nelayan, justru merasa dirugikan. Nelayan di 16 desa yang terdampak kehilangan akses ke laut, yang merupakan sumber utama penghidupan mereka.
Kondisi ini semakin parah karena adanya intimidasi terhadap kelompok masyarakat yang menolak keberadaan pagar tersebut. Tekanan ini mencerminkan bagaimana proyek ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mencederai hak-hak masyarakat setempat. Konflik ini perlu segera diselesaikan melalui dialog yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait.
Solusi dan Langkah Ke Depan
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah memiliki peran untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas proyek ini. Pemerintah harus menindak tegas pihak yang melanggar hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam penerbitan sertifikat ilegal.
Selain itu, diperlukan pendekatan partisipatif untuk menyelesaikan konflik sosial yang ada. Pemerintah perlu mengadakan forum dialog yang melibatkan masyarakat terdampak, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, pemerintah bersama lembaga konservasi harus memulihkan ekosistem yang rusak akibat pembangunan pagar laut.
Pembangunan pagar laut di Tangerang mencerminkan lemahnya tata kelola, baik dari sisi hukum, lingkungan, maupun sosial. Selain itu, ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab, konflik antar masyarakat, serta kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan matang. Pemerintah harus segera bertindak dengan menegakkan hukum, memulihkan lingkungan, dan menyelesaikan konflik sosial agar tidak ada pihak yang dirugikan lebih jauh.
Melalui langkah-langkah tersebut, penulis berharap agar tidak terjadi kejadian serupa dimasa yang akan datang, dan pembangunan di kawasan pesisir dapat dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. (***)
Penulis Adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan